- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Cara Menghitung Rating Program TV
TS
lionsartha
Cara Menghitung Rating Program TV
Quote:
Mudah-mudahan ini nggak REPOST dan bermanfaat, karena ini muncul karena rasa penasaran mengapa acara TV banyak yang kurang mendidik. TS tidak menolak  tapi jangan di
tapi jangan di  karena bacaan yang terlalu panjang. Semoga bermanfaat
karena bacaan yang terlalu panjang. Semoga bermanfaat 
 tapi jangan di
tapi jangan di  karena bacaan yang terlalu panjang. Semoga bermanfaat
karena bacaan yang terlalu panjang. Semoga bermanfaat 
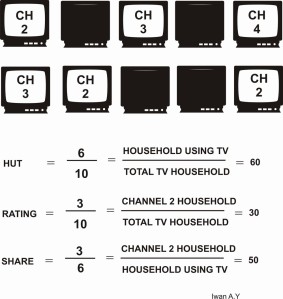
Quote:
Hingga detik ini, kekuatan hegemonik rating sebagai ujung tombak riset audiens televisi di Indonesia ternyata masih sedemikian kokoh. Rating diperlakukan sebagai “malaikat pencatat amal” yang menjadi barometer tunggal seberapa banyak “pahala” (jumlah penonton) dari suatu program acara yang ditayangkan stasiun televisi. Praktik penyiaran televisi di Indonesia selalu mengandalkan sitem rating sebagai pertimbangan untuk menentukan nasib program-program acara, apakah “masuk surga” (terus ditayangkan) atau “masuk neraka” (dihentikan penayanganya).
Bagi televisi, “kualitas” program diukur dari angka rating dan share yang pada akhirnya memengaruhi perolehan iklan. Televisi cenderung berkiblat pada rating dan share yang menentukan layak tidaknya suatu program acara. Rating menjadi faktor utama yang menentukan definisi selera audiens, mutu acara, serta menentukan keputusan dan strategi televisi. Baik-buruk atau nilai-nilai kepatutan menjadi nomor sekian dari hal-hal yang harus diperhatikan di luar pertimbangan rating.
Di tengah pemujaan rating, sistem rating mendapat banyak kritik tajam karena kelemahan-kelemahan praktik metodologis maupun teknis penyelenggaraan survei yang dilakukan. Secara mendasar, rating misalnya tidak mampu menggambarkan perilaku menonton secara mendalam, seberapa fokus pemirsa menonton acara tersebut, representasi penonton Indonesia yang hanya diukur dari sepuluh kota, teknik pengambilan sampel, dinamika pergantian responden (panel), dan sebagainya.
Pembacaan rating oleh pihak televisi, production house (PH), biro iklan-media planner, bahkan masyarakat pada umumnya juga mengalami distorsi makna. Kesalahpahaman ini berangkat dari realitas media yang selalu menonjolkan sudut pandang capaian angka rating dan share untuk menilai kesuksesan atau keberhasilan tayangan TV. Wacana yang keliru mengenai makna rating awalnya bukan hanya berpangkal pada kesalahan media, melainkan adanya dominasi cara pikir instan penyiaran yang diwakili programmer yang bertugas menyusun jadwal acara siaran sehari-hari serta praktisi sales-marketing yang menjual durasi acara kepada pengiklan. Pun dari sisi kredibilitas penyelenggara rating, yakni Nielsen juga sempat dipertanyakan, sebagaimana rumor yang sempat beredar di internet, terutama di milis-milis maupun weblog. Kontroversi yang mengemuka antara lain menyangkut independensi, validitas, ketidakjelasan kompetensi petugas survei-tenaga lapangan dari lembaga yang bersangkutan, sampai remeh temeh soal minimnya imbalan yang diberikan kepada responden, dan sebagainya.[2]
Tulisan ini menelaah polemik seputar rating di tengah gegap gempita industri televisi. Paparan awal mendiskusikan posisi rating dan relasinya dengan motif untuk menarik iklan. Selanjutnya diuraikan mengenai sejarah awal riset audiens televisi, baik dalam konteks kelahirannya di negara asalnya (Amerika Serikat) maupun di Indonesia, serta mekanisme bagaimana rating berfungsi sebagai instrumen riset audiens. Terakhir, penulis mencoba memotret masa depan sistem rating di tengah pesatnya perkembangan teknologi televisi dan konvergensi media.
Bagi televisi, “kualitas” program diukur dari angka rating dan share yang pada akhirnya memengaruhi perolehan iklan. Televisi cenderung berkiblat pada rating dan share yang menentukan layak tidaknya suatu program acara. Rating menjadi faktor utama yang menentukan definisi selera audiens, mutu acara, serta menentukan keputusan dan strategi televisi. Baik-buruk atau nilai-nilai kepatutan menjadi nomor sekian dari hal-hal yang harus diperhatikan di luar pertimbangan rating.
Di tengah pemujaan rating, sistem rating mendapat banyak kritik tajam karena kelemahan-kelemahan praktik metodologis maupun teknis penyelenggaraan survei yang dilakukan. Secara mendasar, rating misalnya tidak mampu menggambarkan perilaku menonton secara mendalam, seberapa fokus pemirsa menonton acara tersebut, representasi penonton Indonesia yang hanya diukur dari sepuluh kota, teknik pengambilan sampel, dinamika pergantian responden (panel), dan sebagainya.
Pembacaan rating oleh pihak televisi, production house (PH), biro iklan-media planner, bahkan masyarakat pada umumnya juga mengalami distorsi makna. Kesalahpahaman ini berangkat dari realitas media yang selalu menonjolkan sudut pandang capaian angka rating dan share untuk menilai kesuksesan atau keberhasilan tayangan TV. Wacana yang keliru mengenai makna rating awalnya bukan hanya berpangkal pada kesalahan media, melainkan adanya dominasi cara pikir instan penyiaran yang diwakili programmer yang bertugas menyusun jadwal acara siaran sehari-hari serta praktisi sales-marketing yang menjual durasi acara kepada pengiklan. Pun dari sisi kredibilitas penyelenggara rating, yakni Nielsen juga sempat dipertanyakan, sebagaimana rumor yang sempat beredar di internet, terutama di milis-milis maupun weblog. Kontroversi yang mengemuka antara lain menyangkut independensi, validitas, ketidakjelasan kompetensi petugas survei-tenaga lapangan dari lembaga yang bersangkutan, sampai remeh temeh soal minimnya imbalan yang diberikan kepada responden, dan sebagainya.[2]
Tulisan ini menelaah polemik seputar rating di tengah gegap gempita industri televisi. Paparan awal mendiskusikan posisi rating dan relasinya dengan motif untuk menarik iklan. Selanjutnya diuraikan mengenai sejarah awal riset audiens televisi, baik dalam konteks kelahirannya di negara asalnya (Amerika Serikat) maupun di Indonesia, serta mekanisme bagaimana rating berfungsi sebagai instrumen riset audiens. Terakhir, penulis mencoba memotret masa depan sistem rating di tengah pesatnya perkembangan teknologi televisi dan konvergensi media.
Quote:
Rating dan Iklan: Penciptaan Kebutuhan Palsu
Sejak keterbukaan informasi dibuka lebar dan banyak stasiun televisi swasta berdiri, televisi Indonesia terkena sindrom snobisme; terjebak dalam selera pasar dengan mendasarkan pada rating acara. Rating menentukan nilai jual program kepada para pengiklan. Semakin tinggi rating sebuah acara, semakin besar pula minat para pengiklan untuk mensponsori acara meskipun dengan harga yang tinggi. Akibatnya, semua stasiun televisi berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin dan bisa menyedot sebanyak mungkin pengiklan.
Teguh Imawan, dalam artikel opininya di Suara Pembaruan, 22 September 2006 menulis, opini publik tentang rating acara televisi selalu dominan diwarnai oleh dua pandangan hipotetis. Pertama, bila acara memiliki rating tinggi, maka otomatis acara tersebut dinilai bagus. Kedua, sebaliknya, suatu program acara divonis tidak bagus jika capaian angka rating tergolong rendah. Akibat lebih jauh dari wacana media yang mengunggulkan rating membuat para sebagian praktisi dan profesional penyiaran, khususnya yang berkecimpung pada produksi tipe program bergenre nonrating, seperti informasi (news) dan acara keagamaan, menjadi turun pamor dan jatuh “harga banderolnya” di mata manajemen TV.
Kondisi ini sejalan dengan pemaparan Mosco tentang kajian ekonomi politik media, yakni praktik media massa saat ini selalu melakukan komodifikasi dengan melakukan serangkaian proses produksi isi media berdasarkan kepentingan pasar (Mosco, 1995: 140-212). Seperti halnya barang dagangan, pengelolaan media sarat akan nilai-nilai ekonomis yang berkiblat pada angka rating, efisiensi dan efektivitas produksi, tiras media, serta pemfokusan target konsumen potensial. Produk media diarahkan untuk menarik perhatian audiens dalam jumlah besar (Mosco, 1995: 140-212). Sejak lama Chesney (1998) mengkritik praktik ini dengan mengatakan bahwa media sekarang menjadikan dirinya sebagai pelayan kepentingan dan kebutuhan pasar daripada kepentingan publik. Penegasan ini tidaklah berlebihan mengingat orientasi produk media hampir semuanya cenderung memenuhi keinginan konsumen dan pemasang iklan. Fakta ini juga semakin mengokohkan posisi khalayak sebagai produk yang dijual kepada pemasang iklan maupun sebagai buruh yang dieksploitasi kalangan industrialis televisi (Lukmantoro, 2008: 59)
Dalam posisi demikian, sulit diharapkan media menjadi bagian dari pembentuk karakter bangsa yang sehat karena institusi media lebih memilih—meminjam istilah Ashadi Siregar—semata-mata menjadi pemasok industri kultural. Dalam industri kultural, produk yang diciptakan selalu berorientasi pada konsumsi massa. Proses produksinya senantiasa mempertimbangkan kepentingan material (modal-uang) dan hiburan (kesenangan). Tester (1994: 40) menyindir kondisi itu sebagai komersialisasi “sampah” yang berbahaya karena berdampak serius pada kualitas hidup manusia.
Bayangkan saja penonton kita mengalami cultural brain wash dengan dicekoki kebutuhan-kebutuhan palsu dengan bentuk-bentuk tontonan yang gersang, tidak edukatif-inovatif, serta lebih banyak menonjolkan melankolisme kehidupan. Contoh sederhana bisa dilihat dari salah satu tayangan yang paling digemari masyarakat, yakni sinetron. Praktik-praktik industri sinetron Indonesia, jika ditilik di luar konteks makro, yakni dari aspek internal produksi dan kebijakan pengelola televisi sendiri, menunjukkan beberapa “penyakit” yang kontraproduktif bagi sebuah karya seni. Ironisnya, praktk-praktik ini justru mewabah bergerak progresif dengan angka capaian rating. Jika dirunut sederhana, penyakit itu antara lain tampak dari hal-hal sebagai berikut: epigon (mengekor), jiplakan, episode yang dipanjang-panjangkan, sekuel yang dipaksakan berlanjut, skenario monoton, adopsi mentah dari luar, menjual wajah tampan/cantik, berkedok religius-meski sebenarnya mengarah pada kesyirikan, memaksakan lagu hits menjadi tema/daya tarik sinetron, banyaknya hal-hal klise ditampilkan, jam tayang yang cenderung seragam, menampilkan unsur SARA, Jakartasentris, bias gender, stereotipe yang berlebihan, mengumbar makian dan umpatan, eksploitasi tubuh perempuan, kekerasan dan sadistis, mistik, dan sebagainya.[3]
Pada perkembangan selanjutnya, kalaupun ada tayangan kontroversial—ber-rating tinggi—dihentikan oleh pengelola televisi, itu terjadi setelah ada keberatan dari masyarakat. Dalam beberapa kasus yang menyangkut acara hiburan misalnya, pihak televisi atau production house mau mendengarnya karena tidak ada pilihan lain. Pihak televisi seolah selalu punya argumen bahwa apa yang mereka tawarkan adalah semata-mata hiburan. Konsep hiburan (entertainment) bagi industri televisi sebagai bahan jualan utama memang sulit dibendung karena secara mendasar, media hiburan memiliki formula yang ampuh untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens (Potter, 2001: 113).
Lebih lanjut, dilihat dari sisi internal media, menurut pandangan Imawan (Suara Pembaruan, 22 September 2006), para pekerja televisi sering mengedepankan pentingnya rating dan share untuk mendongkrak popularitas stasiun televisi. Kepentingan divisional itu membuat pola pikir pragmatis dengan menjadikan angka rating sebagai informasi tunggal untuk menetapkan pola acara dalam konteks persaingan dengan televisi lain. Sementara itu, praktisi sales-marketing berfokus bagaimana secara cepat mampu mengejar dan memenuhi target penjualan spot iklan. Karena tak mau sedikit membuka wawasan menerima kreasi baru program acara, ketika meyakinkan pengiklan agar mau menaruh spot iklan ke acara yang dimaksud, ia hanya mengandalkan semacam “benchmark” dari data yang sudah siap saji. Dalam praktiknya, marketing bermodus kreativitas instan seperti ini cenderung mencari kemudahan mendapatkan klien dengan menyebut nama acara yang sudah ada sebagai cara praktis menggambarkan isi acara yang ditawarkannya kepada pengiklan (Imawan, Suara Pembaruan, 22 September 2006).
Mengapa televisi sedemikian takluk pada rating? Tidak sama dengan media cetak atau media interaktif (internet), televisi memiliki potensial viewer yang sangat besar. Di luar ketegori televisi berlangganan atau televisi kabel, nyaris tidak ada biaya (uang) yang dikeluarkan seseorang untuk menonton televisi. Maka masyarakat penonton televisi Indonesia yang notabene rata-rata berkemampuan ekonomi menengah ke bawah, cenderung memilih mengonsumsi media televisi, dibanding media lainnya. Dalam Media Scene tahun 2005-2006 disebutkan jumlah total penduduk Indonesia adalah 219.898.300 jiwa, sedangkan jumah penduduk di daerah yang terjangkau siaran televisi mencapai 175.296.231 (Siregar: 2007: 35-36). Angka ini tentu menjadi lahan yang sangat subur bagi produsen untuk mempromosikan produknya lewat televisi berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Fakta ini didukung pula oleh kekuatan televisi sebagai media penyampai iklan dengan berbagai kelebihan, terutama kemampuan menggabungkan citra verbal dan nonverbal dalam format audio visual yang mudah diakses sulit ditandingi media manapun. Tak heran bila belanja iklan di televisi jauh mengungguli media lainnya. Pengiklan sangat berkepentingan dengan kemampuan menjangkau jumlah pemirsa sebanyak mungkin terhadap materi iklannya yang disiarkan melalui acara TV, sehingga biaya promosi yang dikeluarkan itu (cost) berpotensi balik dengan jumlah keuntungan (benefit) yang jauh lebih tinggi.
Hasrat beriklan ini mencapai puncaknya pada acara-acara yang berkategori tayang prime time. Menurut Nielsen Media Research (NMR), prime time adalah waktu ketika semua orang sudah pulang ke rumah dan menonton televisi. Terletak antara pukul 19.00 – 21.00 malam. Prime time dipercaya akan menghasilkan rating yang lebih tinggi dibanding waktu lain. Pemahaman ini membuat acara yang tayang pada waktu tersebut menjadi lebih mahal harganya (Panjaitan & Iqbal, 2006: 42). Momen istimewa prime time digunakan televisi untuk menayangkan program acara (sebutlah sinetron sebagaimana disinggung sebelumnya) yang isinya kurang lebih sama. Keseragaman ini bergeser lebih awal pada momen-momen tertentu, misalnya bulan Ramadhan. Akibatnya, publik yang ingin mencari alternatif tayangan tidak diberi kesempatan. Hak publik untuk memperoleh keragaman materi produksi televisi (diversity of content) pada jam-jam tersebut tampaknya diabaikan begitu saja oleh pengelola stasiun televisi.
Sejak keterbukaan informasi dibuka lebar dan banyak stasiun televisi swasta berdiri, televisi Indonesia terkena sindrom snobisme; terjebak dalam selera pasar dengan mendasarkan pada rating acara. Rating menentukan nilai jual program kepada para pengiklan. Semakin tinggi rating sebuah acara, semakin besar pula minat para pengiklan untuk mensponsori acara meskipun dengan harga yang tinggi. Akibatnya, semua stasiun televisi berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin dan bisa menyedot sebanyak mungkin pengiklan.
Teguh Imawan, dalam artikel opininya di Suara Pembaruan, 22 September 2006 menulis, opini publik tentang rating acara televisi selalu dominan diwarnai oleh dua pandangan hipotetis. Pertama, bila acara memiliki rating tinggi, maka otomatis acara tersebut dinilai bagus. Kedua, sebaliknya, suatu program acara divonis tidak bagus jika capaian angka rating tergolong rendah. Akibat lebih jauh dari wacana media yang mengunggulkan rating membuat para sebagian praktisi dan profesional penyiaran, khususnya yang berkecimpung pada produksi tipe program bergenre nonrating, seperti informasi (news) dan acara keagamaan, menjadi turun pamor dan jatuh “harga banderolnya” di mata manajemen TV.
Kondisi ini sejalan dengan pemaparan Mosco tentang kajian ekonomi politik media, yakni praktik media massa saat ini selalu melakukan komodifikasi dengan melakukan serangkaian proses produksi isi media berdasarkan kepentingan pasar (Mosco, 1995: 140-212). Seperti halnya barang dagangan, pengelolaan media sarat akan nilai-nilai ekonomis yang berkiblat pada angka rating, efisiensi dan efektivitas produksi, tiras media, serta pemfokusan target konsumen potensial. Produk media diarahkan untuk menarik perhatian audiens dalam jumlah besar (Mosco, 1995: 140-212). Sejak lama Chesney (1998) mengkritik praktik ini dengan mengatakan bahwa media sekarang menjadikan dirinya sebagai pelayan kepentingan dan kebutuhan pasar daripada kepentingan publik. Penegasan ini tidaklah berlebihan mengingat orientasi produk media hampir semuanya cenderung memenuhi keinginan konsumen dan pemasang iklan. Fakta ini juga semakin mengokohkan posisi khalayak sebagai produk yang dijual kepada pemasang iklan maupun sebagai buruh yang dieksploitasi kalangan industrialis televisi (Lukmantoro, 2008: 59)
Dalam posisi demikian, sulit diharapkan media menjadi bagian dari pembentuk karakter bangsa yang sehat karena institusi media lebih memilih—meminjam istilah Ashadi Siregar—semata-mata menjadi pemasok industri kultural. Dalam industri kultural, produk yang diciptakan selalu berorientasi pada konsumsi massa. Proses produksinya senantiasa mempertimbangkan kepentingan material (modal-uang) dan hiburan (kesenangan). Tester (1994: 40) menyindir kondisi itu sebagai komersialisasi “sampah” yang berbahaya karena berdampak serius pada kualitas hidup manusia.
Bayangkan saja penonton kita mengalami cultural brain wash dengan dicekoki kebutuhan-kebutuhan palsu dengan bentuk-bentuk tontonan yang gersang, tidak edukatif-inovatif, serta lebih banyak menonjolkan melankolisme kehidupan. Contoh sederhana bisa dilihat dari salah satu tayangan yang paling digemari masyarakat, yakni sinetron. Praktik-praktik industri sinetron Indonesia, jika ditilik di luar konteks makro, yakni dari aspek internal produksi dan kebijakan pengelola televisi sendiri, menunjukkan beberapa “penyakit” yang kontraproduktif bagi sebuah karya seni. Ironisnya, praktk-praktik ini justru mewabah bergerak progresif dengan angka capaian rating. Jika dirunut sederhana, penyakit itu antara lain tampak dari hal-hal sebagai berikut: epigon (mengekor), jiplakan, episode yang dipanjang-panjangkan, sekuel yang dipaksakan berlanjut, skenario monoton, adopsi mentah dari luar, menjual wajah tampan/cantik, berkedok religius-meski sebenarnya mengarah pada kesyirikan, memaksakan lagu hits menjadi tema/daya tarik sinetron, banyaknya hal-hal klise ditampilkan, jam tayang yang cenderung seragam, menampilkan unsur SARA, Jakartasentris, bias gender, stereotipe yang berlebihan, mengumbar makian dan umpatan, eksploitasi tubuh perempuan, kekerasan dan sadistis, mistik, dan sebagainya.[3]
Pada perkembangan selanjutnya, kalaupun ada tayangan kontroversial—ber-rating tinggi—dihentikan oleh pengelola televisi, itu terjadi setelah ada keberatan dari masyarakat. Dalam beberapa kasus yang menyangkut acara hiburan misalnya, pihak televisi atau production house mau mendengarnya karena tidak ada pilihan lain. Pihak televisi seolah selalu punya argumen bahwa apa yang mereka tawarkan adalah semata-mata hiburan. Konsep hiburan (entertainment) bagi industri televisi sebagai bahan jualan utama memang sulit dibendung karena secara mendasar, media hiburan memiliki formula yang ampuh untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens (Potter, 2001: 113).
Lebih lanjut, dilihat dari sisi internal media, menurut pandangan Imawan (Suara Pembaruan, 22 September 2006), para pekerja televisi sering mengedepankan pentingnya rating dan share untuk mendongkrak popularitas stasiun televisi. Kepentingan divisional itu membuat pola pikir pragmatis dengan menjadikan angka rating sebagai informasi tunggal untuk menetapkan pola acara dalam konteks persaingan dengan televisi lain. Sementara itu, praktisi sales-marketing berfokus bagaimana secara cepat mampu mengejar dan memenuhi target penjualan spot iklan. Karena tak mau sedikit membuka wawasan menerima kreasi baru program acara, ketika meyakinkan pengiklan agar mau menaruh spot iklan ke acara yang dimaksud, ia hanya mengandalkan semacam “benchmark” dari data yang sudah siap saji. Dalam praktiknya, marketing bermodus kreativitas instan seperti ini cenderung mencari kemudahan mendapatkan klien dengan menyebut nama acara yang sudah ada sebagai cara praktis menggambarkan isi acara yang ditawarkannya kepada pengiklan (Imawan, Suara Pembaruan, 22 September 2006).
Mengapa televisi sedemikian takluk pada rating? Tidak sama dengan media cetak atau media interaktif (internet), televisi memiliki potensial viewer yang sangat besar. Di luar ketegori televisi berlangganan atau televisi kabel, nyaris tidak ada biaya (uang) yang dikeluarkan seseorang untuk menonton televisi. Maka masyarakat penonton televisi Indonesia yang notabene rata-rata berkemampuan ekonomi menengah ke bawah, cenderung memilih mengonsumsi media televisi, dibanding media lainnya. Dalam Media Scene tahun 2005-2006 disebutkan jumlah total penduduk Indonesia adalah 219.898.300 jiwa, sedangkan jumah penduduk di daerah yang terjangkau siaran televisi mencapai 175.296.231 (Siregar: 2007: 35-36). Angka ini tentu menjadi lahan yang sangat subur bagi produsen untuk mempromosikan produknya lewat televisi berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Fakta ini didukung pula oleh kekuatan televisi sebagai media penyampai iklan dengan berbagai kelebihan, terutama kemampuan menggabungkan citra verbal dan nonverbal dalam format audio visual yang mudah diakses sulit ditandingi media manapun. Tak heran bila belanja iklan di televisi jauh mengungguli media lainnya. Pengiklan sangat berkepentingan dengan kemampuan menjangkau jumlah pemirsa sebanyak mungkin terhadap materi iklannya yang disiarkan melalui acara TV, sehingga biaya promosi yang dikeluarkan itu (cost) berpotensi balik dengan jumlah keuntungan (benefit) yang jauh lebih tinggi.
Hasrat beriklan ini mencapai puncaknya pada acara-acara yang berkategori tayang prime time. Menurut Nielsen Media Research (NMR), prime time adalah waktu ketika semua orang sudah pulang ke rumah dan menonton televisi. Terletak antara pukul 19.00 – 21.00 malam. Prime time dipercaya akan menghasilkan rating yang lebih tinggi dibanding waktu lain. Pemahaman ini membuat acara yang tayang pada waktu tersebut menjadi lebih mahal harganya (Panjaitan & Iqbal, 2006: 42). Momen istimewa prime time digunakan televisi untuk menayangkan program acara (sebutlah sinetron sebagaimana disinggung sebelumnya) yang isinya kurang lebih sama. Keseragaman ini bergeser lebih awal pada momen-momen tertentu, misalnya bulan Ramadhan. Akibatnya, publik yang ingin mencari alternatif tayangan tidak diberi kesempatan. Hak publik untuk memperoleh keragaman materi produksi televisi (diversity of content) pada jam-jam tersebut tampaknya diabaikan begitu saja oleh pengelola stasiun televisi.
Quote:
Kontroversi Seputar Rating: Mempertanyakan Akurasi
Permasalahan yang selalu mengemuka mengenai metode rating Nielsen adalah soal akurasi. Ada jutaan televisi yang dimiliki oleh jutaan keluarga di sebuah negara. Sementara, Nielsen hanya mengambil 5000 di antaranya. Apakah sampel sesedikit itu bisa merepresentasikan perilaku menonton masyarakat dengan akurat?
Jawaban dari pertanyaan ini adalah “iya, namun dengan keterbatasan”. Sebuah sampel penelitian tidak perlu terlalu banyak untuk bisa merepresentasikan keseluruhan populasi, selama sampel tersebut representatif. Dominick, dkk (2004: 280) memberi ilustrasi dengan analogi: seseorang yang pergi ke dokter untuk tes darah. Sang dokter tentu tidak perlu mengambil 2 liter darah dari tubuh orang tersebut. Yang diperlukan hanyalah beberapa milimeter saja. Namun dari jumlah yang sedikit itu sang dokter sudah bisa memperkirakan jumlah sel darah merah, tingkat kolesterol, kadar haemoglobin, dan lain-lain.
Sekalipun demikian, hasil rating Nielsen tetap saja tidak bisa tepat sepenuhnya, selalu ada kemungkinan akan sampling error. Survei rating Nielsen memang memiliki validitas internal yang baik karena menggunakan alat ukur canggih yang mampu mengurangi kesalahan masukan data sekecil-kecilnya. Akan tetapi, validitas eksternalnya terlalu lemah untuk sampai bisa megatakan bahwa hasil rating ini mewakili gambaran umum se-Indonesia. Hasil rating harus dibaca lebih spesifik, hanya berlaku untuk kota besar di barat negeri yang tercakup pengukuran ini. Lagipula, sampel tidak meliputi wilayah pedesaan yang justru didiami delapan puluh persen masyarakat Indonesia.Selain itu, 55 persen sampel adalah khalayak Jakarta. Jadi, boleh dibilang masyarakat Jakarta “sangat berkuasa” mempengaruhi jenis tayangan televisi, karena hasil rating menjadi acuan siaran stasiun televisi Jakarta, yang daya pancarnya menjangkau hampir seluruh Nusantara (Prakoso, http://www.semestanet.com/2007/11/22...ing-dilakukan/).
Di Amerika, Nielsen Media Research menggambarkan dua tipe berbeda dalam mengambil sampel saat ingin mengukur aktivitas menonton TV di Amerika Serikat. Pertama, NTI yang didesain untuk merepresentasikan populasi di sebuah daerah. Hasil datanya bertaraf nasional. Sebagai sampel, Nielsen mula-mula memilih acak lebih dari 6000 area di suatu negara, biasanya berpusat pada area urban, lalu mensensus seluruh rumah tangga yang ada di area itu. Setelah itu, 5000 rumah tangga dari seluruh populasi diambil lagi secara acak. Setiap keluarga dihubungi, dan jika mereka bersedia untuk menjadi responden, Nielsen akan memasang People meter.
Prosedur yang hampir sama di Indonesia juga dilakukan oleh AGB Nielsen yang saat ini wilayah suirveinya mencakup 10 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin. Tingkat penyebaran panel (satu set perangkat pencatatan rating pada televisi rseponden) didasarkan pada survei awal atau Establishment Survey (ES) di 10 kota tersebut untuk menetapkan dan mengidentifikasi profil demografi penonton TV. Dari ES, akan didapatkan jumlah rumah tangga (berusia 5 tahun ke atas) yang memiliki TV yang berfungsi dengan baik atau disebut populasi TV. Penyebaran sampel tidak sama di setiap kota, yaitu Jakarta 55 persen, Surabaya 20 persen, Bandung 5 persen, Yogyakarta 5 persen, Medan 4 persen, Semarang 3 persen, Palembang 3 persen, Makassar 2 persen, Denpasar 2 persen, dan Banjarmasin 1 persen. Angka ini proporsional berdasarkan populasi kepemilikan televsisi di tiap-tiap kota itu. Kepemilikan televisi di Jakarta, misalnya, 55 persen terhadap total 10 kota, maka jumlah sampelnya 55 persen.
Penyebaran panel juga didasarkan target pemirsa, misalnya Status Ekonomi Sosial (SES), pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Sama dengan penyebaran panel per area, pembagian panel per SES juga didasarkan atas ES. Jika dari ES tergambar bahwa populasi TV Jakarta sejumlah 19% berasal dari SES A, maka panel SES A yang direkrut pun sebanyak 19% dari total panel Jakarta. Demikian pula, penyebaran panel secara keseluruhan pun didasarkan atas proporsi di tingkat populasi yang persentasenya tentu tidak merata antara kelas atas (26%), menengah (51%), dan bawah (23%).
Dari teknik ES ini banyak yang mempertanyakan mengapa pemerataan pada sebaran datanya, tidak diambil jumlah responden yang seimbang misalnya untuk kelas ekonomi atas 33,3%, kelas ekonomi menengah 33,3 %, untuk kelas ekonomi bawah 33,3%, sehingga total 100%? AGB Nilesen yang saat ini sudah beroperasi di lebih dari 30 negara berargumen bahwa penyebaran panel tidak bisa disamaratakan dengan proporsi masing-masing 33,3% karena yang akan terjadi nantinya justru sampel tidak mewakili populasi.
Pada aspek lain secara teknis pergantian responden selam kurun waktu tertentu juga memengaruhi kualitas dan akurasi survei. Idealnya sebuah keluarga atau sebuah rumah yang menjadi responden televisi menjadi reponden selama 6 bulan saja atau maksimal selama 1 tahun. Setelah itu AGB Nielsen harus mencari responden baru. Secara statistik hal itu perlu dilakukan demi menjaga objektivitas data. Di sisi lain bertujuan agar secara psikologis, mood responden tidak mempengaruhi data selanjutnya.
Perdebatan metodologis mengenai akurasi rating menjadi hal yang wajar mengingat secara mendasar terdapat dua model dasar dalam mempelajari audiens dan media, yakni model efek dan penggunaaan-gratifikasi. Kedua model ini memberikan penekanan yang berbeda. Model efek merujuk pada penekanan kekuatan “pesan” yang disampaikan media kepada audiens sehingga memposisikan audiens seolah-olah pasif, sementara model penggunaan dan gratifikasi memberi penekanan pada apa yang dilakukan audiens terhadap media. Ini menunjukkan otoritas dan kekuatan audiens dalam menggunakan media. Berdasarkan perbedaaan mendasar tersebut, dalam mempelajari riset audiens tidak cukup hanya dengan sistem rating yang mendasarkan pada metode penelitian kuantitatif, yang mengukur semua dimensi bedasarkan angka-angka. Untuk itu perlu digagas alternatif lain selain rating yang hanya berbicara mengenai angka-angka statistik yang kental beraroma positivistik.
Barangkali bukan sesuatu yang baru jika perdebatan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif muncul dengan mengemukakan kelebihan dan kekurangan masing-masing secara membabi buta (Webster, et, al. 2006: 3-4). Pada titik inilah sebenarnya kritik membangun yang direkomendasikan adalah memakai variasi atau menggabungkan keduanya. Menurut Susilaningtyas (2007:197), riset kuantitatif berguna untuk mendapakan gambaran objektif dengan cakupan responden (dalam hal ini audiens) yang lebih besar sebagai sampel dari sejumlah populasi, sementara riset kualitatif digunakan untuk memperdalam temuan empirik di lapangan. Pada beberapa kasus bisa diinterpretasikan sebagai teknik triangulasi, misalnya tindak lanjut dengan FGD yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Bukan FGD “pesanan” atau FGD “formalitas” yang selama ini banyak dijumpai dalam praktik riset audiens di negara kita.
Permasalahan yang selalu mengemuka mengenai metode rating Nielsen adalah soal akurasi. Ada jutaan televisi yang dimiliki oleh jutaan keluarga di sebuah negara. Sementara, Nielsen hanya mengambil 5000 di antaranya. Apakah sampel sesedikit itu bisa merepresentasikan perilaku menonton masyarakat dengan akurat?
Jawaban dari pertanyaan ini adalah “iya, namun dengan keterbatasan”. Sebuah sampel penelitian tidak perlu terlalu banyak untuk bisa merepresentasikan keseluruhan populasi, selama sampel tersebut representatif. Dominick, dkk (2004: 280) memberi ilustrasi dengan analogi: seseorang yang pergi ke dokter untuk tes darah. Sang dokter tentu tidak perlu mengambil 2 liter darah dari tubuh orang tersebut. Yang diperlukan hanyalah beberapa milimeter saja. Namun dari jumlah yang sedikit itu sang dokter sudah bisa memperkirakan jumlah sel darah merah, tingkat kolesterol, kadar haemoglobin, dan lain-lain.
Sekalipun demikian, hasil rating Nielsen tetap saja tidak bisa tepat sepenuhnya, selalu ada kemungkinan akan sampling error. Survei rating Nielsen memang memiliki validitas internal yang baik karena menggunakan alat ukur canggih yang mampu mengurangi kesalahan masukan data sekecil-kecilnya. Akan tetapi, validitas eksternalnya terlalu lemah untuk sampai bisa megatakan bahwa hasil rating ini mewakili gambaran umum se-Indonesia. Hasil rating harus dibaca lebih spesifik, hanya berlaku untuk kota besar di barat negeri yang tercakup pengukuran ini. Lagipula, sampel tidak meliputi wilayah pedesaan yang justru didiami delapan puluh persen masyarakat Indonesia.Selain itu, 55 persen sampel adalah khalayak Jakarta. Jadi, boleh dibilang masyarakat Jakarta “sangat berkuasa” mempengaruhi jenis tayangan televisi, karena hasil rating menjadi acuan siaran stasiun televisi Jakarta, yang daya pancarnya menjangkau hampir seluruh Nusantara (Prakoso, http://www.semestanet.com/2007/11/22...ing-dilakukan/).
Di Amerika, Nielsen Media Research menggambarkan dua tipe berbeda dalam mengambil sampel saat ingin mengukur aktivitas menonton TV di Amerika Serikat. Pertama, NTI yang didesain untuk merepresentasikan populasi di sebuah daerah. Hasil datanya bertaraf nasional. Sebagai sampel, Nielsen mula-mula memilih acak lebih dari 6000 area di suatu negara, biasanya berpusat pada area urban, lalu mensensus seluruh rumah tangga yang ada di area itu. Setelah itu, 5000 rumah tangga dari seluruh populasi diambil lagi secara acak. Setiap keluarga dihubungi, dan jika mereka bersedia untuk menjadi responden, Nielsen akan memasang People meter.
Prosedur yang hampir sama di Indonesia juga dilakukan oleh AGB Nielsen yang saat ini wilayah suirveinya mencakup 10 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin. Tingkat penyebaran panel (satu set perangkat pencatatan rating pada televisi rseponden) didasarkan pada survei awal atau Establishment Survey (ES) di 10 kota tersebut untuk menetapkan dan mengidentifikasi profil demografi penonton TV. Dari ES, akan didapatkan jumlah rumah tangga (berusia 5 tahun ke atas) yang memiliki TV yang berfungsi dengan baik atau disebut populasi TV. Penyebaran sampel tidak sama di setiap kota, yaitu Jakarta 55 persen, Surabaya 20 persen, Bandung 5 persen, Yogyakarta 5 persen, Medan 4 persen, Semarang 3 persen, Palembang 3 persen, Makassar 2 persen, Denpasar 2 persen, dan Banjarmasin 1 persen. Angka ini proporsional berdasarkan populasi kepemilikan televsisi di tiap-tiap kota itu. Kepemilikan televisi di Jakarta, misalnya, 55 persen terhadap total 10 kota, maka jumlah sampelnya 55 persen.
Penyebaran panel juga didasarkan target pemirsa, misalnya Status Ekonomi Sosial (SES), pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Sama dengan penyebaran panel per area, pembagian panel per SES juga didasarkan atas ES. Jika dari ES tergambar bahwa populasi TV Jakarta sejumlah 19% berasal dari SES A, maka panel SES A yang direkrut pun sebanyak 19% dari total panel Jakarta. Demikian pula, penyebaran panel secara keseluruhan pun didasarkan atas proporsi di tingkat populasi yang persentasenya tentu tidak merata antara kelas atas (26%), menengah (51%), dan bawah (23%).
Dari teknik ES ini banyak yang mempertanyakan mengapa pemerataan pada sebaran datanya, tidak diambil jumlah responden yang seimbang misalnya untuk kelas ekonomi atas 33,3%, kelas ekonomi menengah 33,3 %, untuk kelas ekonomi bawah 33,3%, sehingga total 100%? AGB Nilesen yang saat ini sudah beroperasi di lebih dari 30 negara berargumen bahwa penyebaran panel tidak bisa disamaratakan dengan proporsi masing-masing 33,3% karena yang akan terjadi nantinya justru sampel tidak mewakili populasi.
Pada aspek lain secara teknis pergantian responden selam kurun waktu tertentu juga memengaruhi kualitas dan akurasi survei. Idealnya sebuah keluarga atau sebuah rumah yang menjadi responden televisi menjadi reponden selama 6 bulan saja atau maksimal selama 1 tahun. Setelah itu AGB Nielsen harus mencari responden baru. Secara statistik hal itu perlu dilakukan demi menjaga objektivitas data. Di sisi lain bertujuan agar secara psikologis, mood responden tidak mempengaruhi data selanjutnya.
Perdebatan metodologis mengenai akurasi rating menjadi hal yang wajar mengingat secara mendasar terdapat dua model dasar dalam mempelajari audiens dan media, yakni model efek dan penggunaaan-gratifikasi. Kedua model ini memberikan penekanan yang berbeda. Model efek merujuk pada penekanan kekuatan “pesan” yang disampaikan media kepada audiens sehingga memposisikan audiens seolah-olah pasif, sementara model penggunaan dan gratifikasi memberi penekanan pada apa yang dilakukan audiens terhadap media. Ini menunjukkan otoritas dan kekuatan audiens dalam menggunakan media. Berdasarkan perbedaaan mendasar tersebut, dalam mempelajari riset audiens tidak cukup hanya dengan sistem rating yang mendasarkan pada metode penelitian kuantitatif, yang mengukur semua dimensi bedasarkan angka-angka. Untuk itu perlu digagas alternatif lain selain rating yang hanya berbicara mengenai angka-angka statistik yang kental beraroma positivistik.
Barangkali bukan sesuatu yang baru jika perdebatan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif muncul dengan mengemukakan kelebihan dan kekurangan masing-masing secara membabi buta (Webster, et, al. 2006: 3-4). Pada titik inilah sebenarnya kritik membangun yang direkomendasikan adalah memakai variasi atau menggabungkan keduanya. Menurut Susilaningtyas (2007:197), riset kuantitatif berguna untuk mendapakan gambaran objektif dengan cakupan responden (dalam hal ini audiens) yang lebih besar sebagai sampel dari sejumlah populasi, sementara riset kualitatif digunakan untuk memperdalam temuan empirik di lapangan. Pada beberapa kasus bisa diinterpretasikan sebagai teknik triangulasi, misalnya tindak lanjut dengan FGD yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Bukan FGD “pesanan” atau FGD “formalitas” yang selama ini banyak dijumpai dalam praktik riset audiens di negara kita.
Quote:
Lanjut bawah gan 

0
73.3K
Kutip
75
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan